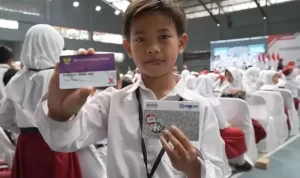Inionline.id – Judul Buku: Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia; Penulis: Haidar Bagir; Penerbit: Mizan Pustaka, September, 2019; Tebal: 212 halaman
Tiap kali membaca buku-buku pendidikan, kita perlu memperhatikan satu hal: saat menulis, penulisnya membayangkan untuk dibaca oleh para guru pengajar-pendidik atau untuk dibaca para murid yang diajar-dididik? Tentu banyak sekali buku pendidikan yang ditujukan kepada guru. Yang sangat menarik adalah jika buku pendidikan yang ditujukan kepada guru itu dibaca dengan perspektif alam pikiran murid.
Buku Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia ini, yang ditulis Haidar Bagir yang sudah 20 tahu menjadi Ketua Yayasan Lazuardi, hampir pasti diperuntukkan untuk para guru pengajar-pendidik. Dengan pembacaan dari perspektif murid, buku ini jadi sangat keras mengkritik paradigma pedagogis yang digunakan guru dalam mengajar-mendidik.
Pertama, prioritas utama pendidikan-pengajaran masih terlalu didominasi sains sebagai ilmu yang bakal mensukseskan kemakmuran anak didik. Prioritas dan paradigma IQ ini punya efek psikologis negatif bagi siswa yang tidak masuk jurusan IPA sebagai siswa kelas dua bahkan siswa bodoh. Hancur rasa harga dirinya (self-esteem) dan rasa percaya diri (self-confidence) yang jadi fondasi penting pendidikan karakter manusia. Entah sudah berapa ribu siswa yang terkena stigma pembodohan ini di Indonesia-bahkan di seluruh dunia.
Tentu saja, paradigma IQ sudah banyak sekali dibantah sejak 1983 saat Howard Gardner memperkenalkan multiple intelligences (MI) dan pada 1995 Daniel Goleman menggebrak paradigma IQ dengan penelitian emotional intelligence atau emotional quotient (EI/EQ). Kata Goleman: sungguh banyak sekali siswa/mahasiswa ber-IQ tinggi justru gagal dalam kehidupan sosial-ekonomi mereka.
Yang kedua, para murid sungguh jarang sekali diapresiasi potensi kecerdasannya yang tentu saja tak melulu IQ. Paradigma multiple intelligences, yang sejak awal melihat berbagai potensi kecerdasan yang dimiliki para siswa, tidak digunakan dalam proses pengajaran-pendidikan. Tak jarang, guru hanya mengistimewakan siswa yang dianggap ber-IQ tinggi saja dan mengeksklusi siswa yang punya kecerdasan emotional quotient atau spiritual quotient.
Guru yang tidak peka pada berbagai kecerdasan biasanya akan menvonis siswa yang tidak ‘patuh’ terhadap eksklusivitas pengajaran-pendidikan sebagai penghalang proses pendidikan-pengajaran, merusak suasana kelas, mengganggu orang belajar.
Paradigma multiple intelligences mengakui bahwa “setiap orang (siswa) memiliki peluang untuk menonjol dalam satu atau lebih kecerdasan.” Proses pendidikan-pengajaran adalah untuk mengakomodasi dan terutama untuk mengembangkan tiap potensi kecerdasan orang/siswa. Tentu saja, pengakuan dan aplikasi pendekatan paradigma multiple intelligences masih belum menjadi paradigma utama bagi mayoritas guru di Indonesia.
Kita masih bisa dengan sangat lumrah mendapati ini: sistem ranking, sistem ujian bahkan sampai tingkat nasional yang sangat IQ-sentris (ini termasuk hasil survei PISA yang sering diagungkan), pola pengajaran “diktatorial” (mendikte dan memonopoli kebenaran), dan belum terbiasa dengan proses pembelajaran berbasis eksperimental atau project based learning (sains, sosial, budaya) yang dikerjakan murid baik secara individual atau kolaboratif dengan sesama siswa atau masyarakat langsung.
Pembongkaran paradigma keguruan dalam praksis pendidikan-pengajaran tentu saja harus memikirkan ulang apa tujuan utama pendidikan-pengajaran. Saat orangtua menyekolahkan anaknya dan saat guru mengajar-mendidik muridnya, apakah semata-mata untuk kesuksesan kesejahteraan material si murid atau untuk kebahagiaan kesejahteraan spiritual, psikologis, dan material anak didik? Anak kaya raya atau anak bahagia?
Jawaban atas pertanyaan ini sangat fundamental sebagai panduan pendidikan-pengajaran, meski sering direcoki oleh imperatif negara modern yang menginginkan warganya patuh pada aturan negara dan terutama agar mengikuti hasrat negara kepada kesejahteraan duniawi semata.
Jika kita refleksikan apa yang ditulis Haidar Bagir dalam buku ini selain masalah pengajaran agama, kita menyadari bahwa ada kekecewaan besar terhadap paradigma keguruan-kesekolahan dalam sistem pendidikan-pengajaran di Indonesia. Masalah ini menjadi semakin runyam karena pada tahun 1990-an hampir semua Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) negeri di Indonesia berubah menjadi universitas. Satu peristiwa akbar dalam sejarah pemikiran pedagogi di Indonesia dengan segala efek negatif dan positifnya.
Yang tak kalah penting, apa pun yang dipikirkan dan diucapkan para ahli pendidikan atau terutama menteri pendidikan yang terus berubah-ubah, masalahnya selalu bisa dikembalikan kepada pertanyaan sederhana: apa sih paradigma pedagogis (ta’dib) yang mendasari proses pendidikan-pengajaran yang dipraktikkan para guru di sekolah?
Masalah utama pendidikan bukanlah para murid, tapi justru para guru, guru, dan sekali lagi guru. Atau, dengan kata lain, sebaiknya kita mulai memikirkan perihal ujian nasional kompetensi keguruan bagi guru daripada heboh perihal ujian nasional bagi siswa.
“Kegagalan akademis siswa bukanlah akibat tidak ada atau kurangnya upaya oleh sekolah, melainkan justru akibat ‘ulah’ sekolah,” kata John Holt dalam buku How Children Fail seperti dikutip Haidar Bagir.